MANUSIA DAN KEGELISAHAN
Demi hari
yang tak pernah melengos, laju lurus waktu, tak pernah mundur. Di belahan bumi
yang gelap aku duduk di atas batu pinggiran daratan luas, angin malam menyergap
kegalisahan, bulan dan bintang menemani sepi, yang sendiri. Kelelawar
seliweran, satu dari mereka menghampiriku.
“Hai orang
yang gelisah. Buatlah gelisahmu jadi penasaran, itu lebih baik agar kau mau
bergerak, dari pada kau hanya berputar-putar dengan kagalisahanmu, diam dan
cuma mendengarkan cerita kegelisahmu itu.”
“Apa
maksudmu, kelelawar. Apa itu kata pendahuluanmu untuk menyampaikan sesuatu
padaku, berita malam apa yang kau bawa.”
“Ya, memang.
Seharusnya kau sudah bisa menebak kabar ini, karena kegelisahanmu sudah cerita
berkali-kali padamu. Di daratanmu akan acara yang mengundang banyak orang,
acara penyunting jilidan lontar seorang petapa.”
“Ya, itu aku
tahu. Tapi apa yang mengharuskan kegelisahan ini ku jadikan penasaran. Biasa
sajakan, setiap acara seperti itu pasti mengundang banyak orang dan bahkan dari
luar daratan ini.”
“O, masih
belum kau sadari juga cerita kegelisahmu, bahwa ada petanda yang akan datang
padamu dan petanda itu dibawa oleh seseorang dari meraka yang datang ke acara itu, mereka yang berasal dari
daratan seberang. Seseorang itulah yang harus jadi penasaranmu yang nanti kau
tunggu, kau cari, kau temukan. Dialah yang membawa petanda itu.”
“Siapa dia,
dan petanda apa yang ia bawa?”
“Carilah
sendiri dan tanyakan pada dia petanda apa yang ia bawa untukmu. Sudahlah, aku
pergi, aku tak mau kau buat malam ini sia-sia untuk membicarakan hal itu
denganmu, mangsaku sedang menantiku.”
“Hai
kelelawar, jangan pergi dulu!”
“Cari saja
sendiri, usahalah sedikit” kelelawar itu pun melesat pergi.
Pagi ini
lebih cerah dari biasanya, seakan langit membocorkan udara surga ke bumi.
Seperti pagi-pagi yang lalu, aku sudah duduk jigang di warung pinggir jalan
simpang tiga belakang rumahku, menyeduh kopi pahit dan mencumbui rokok menthol
kesukaanku. Lalu lalang pengguna jalan sudah jadi pemandangan yang biasa, jika
ada yang kenal ya saling sapa, kalau tak kenal ya ku lihat cuek dia berlalu.
Disaat seruputan terakhir yang paling nikmat, ada yang menyapaku,
“Hai kawan,
tumben wajah gelisahmu tak seperti biasanya.”
“Hai kau,
tahu apa kau tentang wajah gelisahku, kau hanya seekor anjing khafilah yang
tinggal di pendopo pendeta agung. Kawan, aku sekarang tak hanya gelisah yang
diam, tapi juga penasaran yang bergerak untuk berusaha menanti dan mencari
seseorang.”
“Augh…… walau aku seekor anjing, tapi anjing yang
lebih tahu darimu. Augh…. Siapa seseorang itu?”
“Dia salah
satu orang yang akan menghadiri penyunting jilidan lontar sang petapa besok
malam.”
“Augh…. Pasti seseorang yang membawa petanda untukmu,
seseorang yang sering kudengar dari cerita kegelisahanmu. Tapi, bagaimana kau
yakin dapat menemukan dia?”
“Aku yakin
karena kegelisahanku tak pernah meleset, lagi pula aku juga dapat kabar dari
kelelawar semalam.”
“Augh….
Begitu. Baiklah, selamat menunggu, penasaran!”
“Kawan, apa
kau tahu tentang dia? Barang kali kau pernah dengar dari tuanmu atau sang
pendeta itu.”
“O, tidak.
Augh…. Sudah jangan tanya lagi, percuma aku tak tahu apa-apa tantang dia. Kalau
pun tahu aku tidak akan memberi tahumu. aku pergi dulu, kawan.”
Apapun yang
terjadi, aku yakin kegelisahanku akan menemukan muaranya, dan penasaranku juga
akan terjawab dengan kedatangnya yang memberitahukan patanda untukku. Walau aku
tahu akan ada kegelisahan lain yang muncul setelah itu. Suasana sore yang
cantik berpoles jingga di kaki langit barat yang menelan matahari, semakain
membuatku tak sabar menanti saat-saat itu yang tinggal semalam. O, begitu
romantisnya rasa kegelisahan, penasaran membeku dalam lamunan yang terindah.
Daun jatuh dipelataran pendopo pendeta agung berbisik padaku sebagai pesan
terakhirnya, “Hai orang penasaran. Demi jinggaku sayang, angin menitipkan salam
dari dia padaku untukmu. Semalam nanti dia akan berangkat dari daratan dengan
kereta sarden ke daratan ini.”
Demi waktu
jingga yang menghitam, malam yang hitamnya gagah mendekap putih bulan dan
kerlip bintang, aku merasa jabatan tangan telah terjadi bersama pesan yang
disampaikan daun padaku. Seperti malam yang kemarin, aku duduk diatas batu
pinggiran daratan luas, angin menyergap kegelisahan, sepi, yang sendiri. Walau
berkali-kali mendengar cerita kegelisahan yang sama, aku tak merasa jemu,
sampai hari yang ditunggu tiba.
Pekat malam,
hitamnya sayang, inilah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. “Gong… gong…
gong….” Suara gong menara padepokan, tepat sebelah kiri pendopo pendeta agung
bergema ke seluruh penjuru daratan, sebagai tanda acara penyunting jilidan
lontar sang petapa akan dimulai di pendopo itu. Semua orang pun berduyun-duyun
datang, orang-orang sekitar daratan ini maupun daratan seberang berkumpul,
duduk sama rata bersila tanpa perbedaan.
Tepat pada waktu yang telah ditentukan, Uboh rampe, hidangan di suguhkan
dan segala keperluan disiapkan. Ketika suasana hikmat, acara pun dimulai.
Kehikmatan
suasana dalam acara itu membuatku tak nyaman. Aku terus digerus kegelisahan,
penasaran membuatku gusar tak karuan. Ditengah acara yang panjang, kejenuhan
pun menghinggapi sebagian dari mereka yang ada dibarisan belakang, suasana
mulai riuh, lalu melunjak gaduh oleh canda tawa, yang tak membuat barisan depan
kehilangan khusyuknya. Itu sudah wajar terjadi. Kesempatan bagiku, yang juga di
barisan belakang, ikut mengalir kegaduhan canda tawa mereka sembari mencari
tahu tentang seorang pembawa petanda untukku. Kemudian mereka memberitahukan ku
sebuah nama dan orangnya, ya, seseorang yang kumaksud.
Sejenak aku
diam, kupandangi saja dia sambil mendengar kegelisahanku mengiyakan, bahwa
dialah sang pembawa petanda. Lalu aku mencari cara, bagaimana aku bisa
mendekatinya. Sekali ku coba melewatinya, untuk mengambil beberapa cangkir
kopi. Tapi masih belum ku dapati caranya. Ku amati lagi, sambil menikmati kopi
dan sebatang rokok. Ya, aku dapat, dan ini pasti berhasil. Aku yakin. Lalu ku
temui cantrik padepokan yang ku kenal baik, yang duduk bersebelahan dengan dia
dan sedikit babibu ku yang ramah, cukuplah jadi alasan.
“Ae…
cantrik. Maaf, aku tidak bisa membantu banyak untuk acara ini”
“O, tak
apalah. Dengan kehadiranmu pun sudah membantu.”
“Boleh aku
diperkenalkan dengan……!?” dengan
setengah berbisik,
“O ya,
kenalkan, dari daratan seberang”
“Hai, aku
Nanda.”
“Kuprit.” Ku
sebut namaku di perkenalan yang wajar, lalu jabatan tangan yang bukan sekedar
rasa dari kegelisahan, nyata. Keakraban dari setiap perbincangan yang mengalir,
membuat lupa kekhusyuan acara. Ku tawarkan rokok menthol padanya, kebetulan
juga dia suka.
Waktu terus
menggelinding, percakapan kami makin asyik, tak terasa acara pun usai, suasana
jadi gaduh riuh. Ada yang bergegas pamit, ada yang masih ditempat untuk sekedar
beramah tama, membaur keakraban satu sama lain. Yang belum kenal jadi kenal, yang
belum dekat hubungannya jadi lebih akrab. Sedangkan para cantrik sibuk
membereskan seluruh perlengkapan yang telah dipakai, dan mengemasi
barang-barang ketempatnya masing-masing. Aku tak bergegas pulang, karena masih
ada yang harus ku cari, tanda yang dibawa Nanda. Aku turut membaur ditengah
para cantrik yang di pendopo, bersama orang-orang daratan seberang.
Pagi datang,
hitam malam lenyap disapu matahari dengan sinarnya. Aku pun pamit pulang, berjalan gontai, tubuhku lemas, tenaga yang
terkuras begadang semalam bersama para cantrik, ngobrol dengan Nanda. Sesampai
di rumah, aku merasakan kegelisahanku menjerat semakin erat, terasa begitu beda
kali ini. O. aku yakin, inilah kegelisahan lain yang datang, yang sudah aku
kira sebelumnya, kegelisahan baru setelah pertemuanku dengan Ciput. Ah, apa aku
ini, kegelisahan yang bercampur bingung, mencari sesuatu yang belum pernah aku
temui. Ya, aku harus menemui dia kembali untuk memastikan tanda apa yang dia
bawa untukku, aku tak perlu khawatir, dia bilang akan tinggal di daratan ini
beberapa hari, dan semalampun aku sudah sengaja membuat sedikit ikatan emosi.,
dengan membuat janji mengantarkan dia jalan-jalan ke taman pelangi dan
mengarungi telaga endut yang menjadi terkenal di daratan ini.
Saat pagi
sebentar siang, aku duduk di teras rumah, aku mendengarkan cerita dari
kegelisahan baruku untuk pertama kali, aku meyakininya sebagai petunjuk
mengetahui tanda yang dibawa orang dari negeri seberang itu, seperti aku
meyakini cerita kegelisahanku sebelumnya. Tapi, keyakinan itu terbentur
kebingungan yang tak jelas arahnya. Untuk apa tanda itu dan bagaimana rupa
tanda itu, tak jelas ku ketahui dari cerita kegelisahanku.
“Hai, orang
gelisah!” suara yang tak ku hiraukan, entah siapa dan darimana suara itu.
“Hai, orang
gelisah!” suara itu lebih keras memanggilku, yang menyita perhatianku.
“Hai, siapa
yang memanggilku itu?” balasku.
“Aku,
disini, disamping kakimu, ini si lalat yang memanggilmu. Aku memperhatikanmu
sejak tadi, apa sebenarnya yang kau gelisahkan?”
“Eh, kau si
lalat. Untuk apa kau bertanya tentang kegelisahanku.”
“barang kali
saja aku bisa membantumu untuk mencari jalan keluar dari kegelisahanmu itu. Aku
hanya kasihan saja padamu. Kita hidup saja, sudah susah, apalagi ditambah
dengan kegelisahan yang membuat mandegnya perjalanan kita meneruskan hidup, ya
paling tidak itu menyita, dapat kesia-siaan saja. Kasihan.”
“Tahu apa
kau tentang kegelisahanku, aku takkan memberitahu siapapun tentang
kegelisahanku, dan juga kau. Kau tak perlu berkhotbah tentang hidup didepanku”
“Brrrr…. hai
kawan, tak perlu emosi. Aku hanya mengingatkan saja, bahwa kegelisahan hanya
membebani hidup kita saja.”
“O,
begitukah pendapatmu tentang kegelisahan. Ku hargai pendapatmu dan terimakasih
kau mengingatkan aku. Tapi sayang, aku tak perlu mendengarkanmu. Hidupmu saja
tak punya warna, bagaimana kau mengerti tentang kegelisahan dalam hidup. Kau
hanya bisa membuat kegelisahan, dengan berseliweran membuat suara berisik dan
hinggapi makanan-makanan setelah kau hinggapi kotoran, jijik.”
“Brrrr…. Wessst. Emosi!? Lalu apa pendapatmu tentang
kegelisahan itu sendiri, sehingga kau anggap itu adalah warna untuk kau
torehkan diatas kanvas, untuk membuat penggalan pesan dalam sejarah hidupmu,
agar kau dianggap aktor sandiwara top, padahal kau tak berarti apa-apa dalam
catatan kehidupan, yang begitu panjang dan melelahkan untuk di eja.”
“Haah…
berisik! pusing, pusing kepalaku ini mendengarkan ocehanmu.” Lalu aku pergi
meninggalkan lalat itu.
“Ting tang….
Ting tang…” jam 2 siang, aku bergegas
pergi menemui Nanda untuk memenuhi janjiku. Aih… kesempatan. Ku hampiri dia
yang sudah menunggu di depan gapuro pendopo, siap untuk menjejakkan kaki,
menelusuri jalan menuju taman pelangi dan telaga endut. Langkah demi langkah
jejak kami menindih jejak lama, menghentak tanah seperti membuat prasasti
kesaksian pada bumi. Suara-suara kami ditangkap dengan sigap oleh angin dan
dihempaskan ke segala penjuru lalu di tempelkan di setiap permukaan daun-daun,
bagaikan ukiran dinding goa. Ada warna-warna yang muncul begitu saja menghiasi
sayap-sayap peri, hitam-putih, biru-jingga, merah-ungu bermotif batik seperti
kupu-kupu yang baru bebas dari serat
kepompongnya, terlihat begitu indah di taman pelangi.
Angin berhembus
romantis, terasa begitu mesra membelai tubuh kami saat duduk berdua di tepi
danau endut yang nampak berkilau jingga, kejernihan sempurna memantulkan warna
senja. Terbius decak kagum pada alam, demi Tuhan yang telah menciptakan
keindahan dengan guratan-guratanNya yang tak pernah mampu dibaca sempurna oleh
manusia. Cita rasa Sang Maha Indah takkan pernah tertandingi. Di luas langit,
ada puncak rasa-rasa yang terbang bersama burung-burung pipit yang kembali ke
sarangnya diatas pohon. Lelah perjalanan tak mampu menembus kepuasan rasa pada
hati yang disemai bunga oleh peri-peri.
Demi malam
yang hitamnya gagah memeluk bulan dan kerlip bintang, putihnya semakin mempesona, aku antar dia
kembali ke pendopo, melepas lelah semalam lagi sebelum kembali dia pamit.
Serabut bayangannya menerobos mimpi, sungguh ia membuat jaring di sudut ruang,
seperti laba-laba hitam mencuri cela angin-angin kamarku. Malam ini, aku sedang
tak ingin duduk diatas batu. Aku ingin semalam ini hanya dalam kamarku, duduk
menghadap kanvas putih dan mengoleskan warna-warna kegelisahan, yang tak pernah
menemukan muaranya. Ku gambar tanda-tanda itu sebagai penggalan cerita terindah
sepanjang suratan napasku.
Perpisahan
setelah pertemuan sudah wajar harus
diterima, rela atau tidak rela, kulepas kepergiannya dengan do’a, kembali ke
daratan asalnya. Demi waktu yang akan berakhir tanpa akhiran, cerita-cerita
kegelisahan itu kosong dan akan tetap sama hingga kegelisahan bertemu muaranya.
Sumber : http://www.kapasitor.net/id/cerpen/post/2002
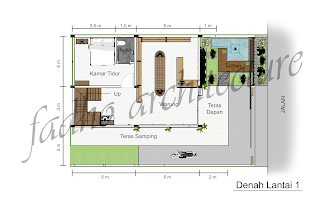
Komentar
Posting Komentar